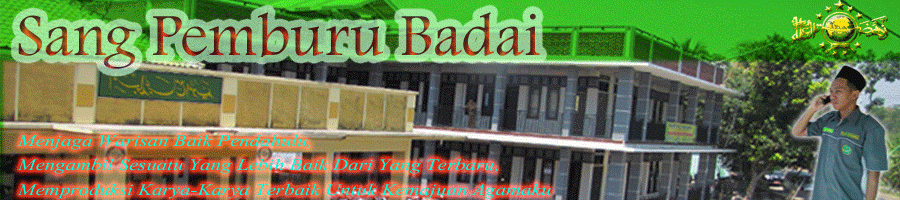Oleh M. Najmuddin Huda Ad-Danusyiri (Julius Hisna)
*Makalah ini disampaikan dalam Eliminasi Debat Kontitusi Mahasiswa Nasional Antar Perguruan Tinggi tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 24-26 Mei 2015.
BAB
I
Pendahuluan
Kekuasaan
kehakiman sebagai kekuasaan negara berdampingan secara horizontal dengan
kekuasaan negara lainnya yang dalam UUD 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini berarti bahwa UUD 1945 telah menentukan bahwa
kekuasaaan kehakiman memiliki kedudukan sebagai kekuasaan negara yang
implementasinya secara subtantif dipegang oleh Mahkamah Agung dan lain-lain
badan kehakiman serta Mahkamah Konstitusi. Diaturnya kehakiman dalam bab
tersendiri dengan 19 ketentuan dapat ditafsirkan bahwa kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan negara yang mandiri (otonom) dan tidak ada keharusan
baginya untuk, baik diperintah maupun memerintah, membantu maupun mendampinngi
kekuasaan pemerintahan negara (Hoesein, 2013:78).
Ketentuan
mengenai kekuasaan kehakiman jelas berbeda dengan ketentuan yang mengatur
tentang kekuasaan negara lainnya, seperti kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar
atas hukum. kekuasaan menurut Ibnu Kholdun diartikan sebagai kemampuan pelaku
untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah
laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai
kekuasaan (Hoesein, 2013:79).
Membicarakan
kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari persoalan, baik
penegakan hukum maupun penemuan hukum, karena keduanya merupakan fungsi dari
kekuasaan kehakiman. Persoalan penegakan hukum merupakan konsekuensi dari
prinsip-prinsip yang diatur dalam negara hukum, sehingga kekuasaan negara
diciptakan, diatur, dan ditegakkan oleh suatu perangkat hukum. Pandangan
tersebut sebagai pembatasan dari suatu kekuasaaan negara sehingga terhindar
dari kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Kedudukan dan
fungsi kekuasaan kehakiman merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan satu
dengan yang lainnya, karena fungsi kekuasaan itu dapat dijalankan jika lembaga
memiliki kedudukan tertentu dalam kekuasaaan (negara), sehingga ia memiliki
kewenangan dan dapat mengimplementasikan secara bertanggung jawab. Hal itu
berarti kedudukan kekuasaan kehakiman juga akan berkaitan dengan kekuasaan
negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan merupakan susunan ketatanegaraan
yang masing-masing memiliki kedudukan, susunan, tugas dan wewenang sebagai
lembaga negara (Hoesein, 2013:78).
Amandemen
UUD 1945 telah memberikan perubahan di bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan
yudikatif yang sangat mendasar. Perubahan tersebut diantaranya adalah kekuasaan
kehakiman tidak lagi hanya mejadi monopoli Mahkamah Agung dengan badan-badan
peradilan di bawahnya, melainkan juga oleh Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari
berbagai kritik yang tak mungkin di hindari haruslah di akui bahwa pada saat
ini dapat di katakan bahwa MK menjadi kiblat dalam penegakan supermasi
konstitusi; artinya hampir setiap ada masalah konstitusi masyarakat selalu
berpaling ke MK. Keadaan tersebut di sebabkan oleh keberanian MK melakukan
ijtihad dalam pengujiaan undang-undang maupun dalam memutus sengketa kewenangan
dan sengketa hasil pemilu.
Namun, dari performance MK yang
seperti itu kemudian timbul harapan yang terlalu besar kepadanya sehingga keraplah
masyarakat bertanya dan meminta MK memutus hal-hal yang di luar kewenangannya.
Alasan berpalingnya seseorang kepada MK adalah selain terlalu banyak berharap
kepada MK tanpa tahu persis lingkup kewenangannya dapat juga di sebabkan oleh
adanya masalah pelanggaran hak konstitusional, tetapi tidak ada instrumen hukum
yang jelas untuk menyelesaikan atau memperkarakannya atau tidak ada penyaluran
penyelesaiannya.
Salah
satu hal yang menjadi permohonan banyak orang di luar kewenangan MK adalah
tentang Constituional Complaint. Constitutional Complain
adalah pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitutional yang tidak
ada instrumen hukum atasnya untuk
memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum
(peradilan). Banyak kalangan yang mengusulkan Constitutional Complain
untuk ditambahkan sebagai salah satu tugas MK. Akan tetapi dalam hal ini banyak
kalangan yang berbeda pendapat apakah penambahan tugas dan wewenang MK tersebut
harus dimasukkan dalam amandemen UUD 1945 ataukah cukup melalui revisi di UU
tentang MK. Kemudian masih juga banyak kalangan yang belum sepakat sejauh
manakah Constitutional Complain tersebut dapat diterapkan. Kedua
permasalahan inilah yang coba kami angkat dalam makalah kami.
BAB
II
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
A.
Mahkamah Konstitusi (MK) Sebagai Amanah UUD 1945
Fondasi
yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah demokrasi berkelanjutan (a
sustainable democrary) adalah sebuah negara konstitusional (constitusional
state) yang bersandar kepada sebuah konstitusi yang kokoh yang dapat
melindungi dirinya dari ancaman, baik dari dalam maupun luar pemerintahan.
Konstitusi yang kokoh yang mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan hanyalah
konstitusi yang mampu mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan
kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial secara seimbang dan saling
mengawasi (checks and balances), serta memberi jaminan yang cukup luas
bagi hak-hak warga negara dan hak-hak asasi. Konstitusi yang kokoh bagi sebuah constitusional
state yang mampu menjamin demokrasi yang berkelanjutan juga harus merupakan
konstitusi yang legimate, dalam arti pembuatannya harus secara
demokratis, diterima dan didukung sepenuhnya oleh seluruh komponen masyarakat
dari berbagai aliran dan faham, aspirasi dan kepentingan (Fadjar, 2006:6).
Amandemen
UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah memberikan perubahan di bidang
kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif yang sangat mendasar. Perubahan
tersebut diantaranya adalah kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya mejadi
monopoli Mahkamah Agung dengan badan-badan peradilan di bawahnya, melainkan
juga oleh Mahkamah Konstitusi. Saat ini dapat di katakan bahwa MK menjadi
kiblat dalam penegakan supermasi konstitusi; artinya hampir setiap ada masalah
konstitusi masyarakat selalu berpaling ke MK. Keadaan tersebut di sebabkan oleh
keberanian MK melakukan ijtihad dalam pengujiaan undang-undang maupun dalam
memutus sengketa kewenangan dan sengketa hasil pemilu.
Pada
dasarnya perubahan konstitusi harus berlandaskan pada nilai-nilai paradigmatik
yang timbul dari tuntutan perubahan itu sendiri. Melalui paradigma perubahan
akan dapat dijelaskan perbedaan penting antara konstitusi lama dengan konsep
perubahan yang diinginkan. Paradigma itu mencakup nilai-nilai dan
prinsip-prinsip penting yang mendasar atau jiwa perubahan konstitusi. Nilai dan
prinsip itu dapat digunakan untuk menyusun telaah kritis terhadap konstitusi
lama dan sekaligus menjadi dasar bagi perubahan konstitusi atau penyusunan
konstitusi baru (Fadjar, 2006:14).
Amandemen
UUD 1945 telah memberikan perubahan di bidang kekuasaan kehakiman atau
kekuasaan yudikatif yang sangat mendasar. Perubahan tersebut diantaranya adalah
kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya mejadi monopoli Mahkamah Agung dengan
badan-badan peradilan di bawahnya, melainkan juga oleh Mahkamah Konstitusi.
Kehadiran Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban
seprti dalam pasal 24C UUD 1945, yaitu:
1.
Menguji
UU terhadap UUD 1945.
2.
Memutus
sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.
3.
Memutus
pembubaran partai politik.
4.
Memutus
perselisihan hasil pemilu.
5.
Wajib
memutus pendapat DPR tentang impeachment terhadap presiden.
Selain itu,
perubahan tersebut juga memberikan
penegasan tentang judicial review, yaitu bahwa pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh
MA. Sedangkan untuk pengujian tentang konstitusionalitas undang-undang
dilakukan oleh MK.
Berdasarkan
ketentuan pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK
mempunyai kedudukan sebagai berikut:
1.
Merupakan
salah satu lembaga negara yang melakukan keuasaan kehakiman.
2.
Merupakan
kekuasaan kehakiman yang merdeka.
3.
Sebagai
penegak hukum, dan keadilan.
Sedangkan tugas
dan fungsinya adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi
tertentu dalam rangka menjaga konstitusi (UUD 1945) agar dilaksanakan secara
bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
B.
Constitutional Complain
Sebagai Wewenang MK
Menurut
Mahfudz M.D. (2010:287) Constitutional Complain adalah pengajuan
perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitutional yang tidak ada instrumen
hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian
hukum (peradilan). Constitutional Complain juga bisa dilakukan
atas adanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang langsung
melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD. Begitu juga bisa dijadikan
objek Constitutional Complain adalah putusan pengadilan yang
melanggar hak-hak konstitusional padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih
tinggi; misalnya adanya putusan kasasi atau herziening (peninjauan kembali)
dari Mahkamah Agung yang ternyata merugikan hak konstitusional seseorang.
Constitutional Complain telah menjadi kewenangan MK di berbagai Negara di
antaranya adalah Mahkamah Konstitusi federal di Negara Jerman. Sebagai Negara
federal German menganut sistem sentralisasi dalam pengujian peraturan
perundang-undangan di mana kewenangan untuk melakukan pengujian hanya
dilekatkan pada MK. Wewenang MK federal dalam memutus perkara Constitutional
Complain adalah terhadap pelanggaran hak-hak dasar dalam konstitusi.
Di Negara
Indonesia sendiri Constitutional Complain belum menjadi salah
satu wewenang di lembaga kekuasaan kehakiman manapun, termasuk MK. Padahal
kebutuhan akan adanya putusan terhadap pelanggaran atas hak-hak konstitusional
warga negara sudah sangat mendesak. Hal ini dikarenakan konstitusi belum
memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap hak konstitusional warga di
karenakan masih terdapat celah hukum. diantara contoh pelangaran hak
konstitusional terjadi pada kasus
Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus menguji pasal 23 ayat 1 UU
No. 4 Tshun 2004 yang menyebutkan bahwa peninjauan kembali (PK) boleh dilakukan
oleh jaksa bertentangan dengan Pasal 263 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 yang
menyebutkan PK hanya oleh terpidana atau ahli warisnya. Uji materi tersebut
tidak dapat mebatalkan putusan MA karena putusan MK bersifat prospektif
(kedepan), sehingga hal ini membatalkan hak konstitusioanl Pollycarpus.
Menyikapi hal ini menurut Mahfudz M.D. yang paling tepat adalah dengan
menggunakan Constitutional Complain.
Dalam era pasca reformasi ini dapat di
katakan bahwa MK menjadi kiblat dalam penegakan supremasi konstitusi, artinya
hampir setiap ada masalah konstitusi masyarakat selalu berpaling ke MK. Keadaan
tersebut di sebabkan oleh keberanian MK melakukan ijtihad dalam pengujiaan
undang-undang maupun dalam memutus sengketa kewenangan dan sengketa hasil
pemilu. Namun, dari performance MK yang seperti itu kemudian timbul harapan
yang terlalu besar kepadanya sehingga keraplah masyarakat bertanya dan meminta
MK memutus hal-hal yang di luar kewenangannya. Padahal dari sudut konstitusi MK
sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menilai hal-hal tersebut.
Berdasarkan ketentuan pasal 24c UUD 1945 MK hanya berwenang melakukan
pengujiaan undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga negara
yang kewenangannya di atur dalam UUD, memutus sengketa hasil pemilu, dan
memutus pembubaran parpol; sedangkan kewajiban MK adalah memutus pendapat atau
dakwaan (impachment) DPR bahwa presiden/ wakil presiden telah melanggar hal-hal
tertentu di dalam UUD 1945 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai
presiden/wakil presiden.
Alasan berpalingnya seseorang
kepada MK adalah selain terlalu banyak berharap kepada MK tanpa tahu persis
lingkup kewenangannya dapat juga di sebabkan oleh adanya masalah pelanggaran
hak konstitusional, tetapi tidak ada instrumen hukum yang jelas untuk
menyelesaikan atau memperkarakannya atau tidak ada penyaluran penyelesaiannya.
Dalam kasus ini, misalnya, tidak jelasnya Surat Keputusan Bersama (SKB) dua
menteri atau lebih dapat di perkarakan ke mana. Jika akan di bawa ke MA melalui
pengujian yudisial peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam UU No.
10 Tahun 2004; jika akan diperkarakan melalui PTUN juga kurang tepat karena isi SKB tersebut dapat di nilai sebagai
pengaturan (bukan penetapan) karena ada muatannya yang bersifat umum. Sedangkan
dari sudut konstitusi MK juga sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk
menilai SKB tersebut atau menjadi keputusan Bokerpakem atau Fatwa Majlis Ulama
Indonesia. Maka seperti dalam kasus SKB tiga Menteri tentang Ahmadiyah kemudian
banyak menimbulkan polemik diantara banyak pihak.
Melihat pada permasalaha diatas maka
sudah sepatutnya kalau Constitutional Complain dimasukkan sebagai
salah satu wewenang MK. Hal ini menjadi sangat penting karena persoalan yang
berhubungan dengan hak-hak konstitutional warga negara ternyata belum semuanya dapat
diselesaikan melalui kewenangan yang dimiliki MK selama ini, terutama
kewenangan Judicial Review. Oleh karena itu Constitutional Complain
dapat dijadikan solusi terhadap kekurangan dan kelemahan yang dimiliki MK
dalam memutus perkara yang berhubungan dengan hak konstitutional warga negara.
Dalam
hal ini terdapat pandangan banyak pihak, apakah kewenangan tersebut dimasukkan
dalam amandemen UUD 1945 atau ke dalam revisi UU MK. Pihak yang mengusulkan Constitutional
Complain menjadi tambahan kewenangan MK dan masuk dalam amandemen UUD
1945 diantaranya Mahfudz MD. Beliau berpandangan bahwa Constitutional Complain
berhubungan erat dengan permasalahan hak-hak dasar warga negara, sehingga
patut untuk dimasukkan dalam UUD 1945. Sedangkan pihak yang mengusulkan Constitutional
Complain cukup masuk dalam revisi UU MK berpendapat bahwa kewenangan
tambahan MK tersebut cukup dimasukkan dalam revisi UU MK. Hal ini disebabkan
karena mengamandemen konstitusi sangatlah sulit, serta harus memperhatikan
struktur, faktor kulrtural dan kondisi negara bersangkutan. Sehingga Constitutional
Complain cukup masuk dalam revisi UU MK, tidak melalui amandemen UUD
1945 (Hukum Online, 2008:1).
Melihat
pada pendapat-pendapat diatas kami lebih setuju bahwa Constitutional Complain
seyogyanya dimasukkan dalam amandemen UUD 1945. Hal ini dikarenakan karena Constitutional
Complain berhubungan erat dengan hak dasar konstituional warga negara
dan harus ada pada kewenangan MK, serta sejajar dengan kewenangan MK yang lain
yang sudah termaktub dalam UUD 1945. Selain itu juga permasalahan yang ada
selama ini belum semuanya dapat diselesaikan dengan melalui kewenangan yang
dimiliki MK selama ini, terutama kewenangan Judicial Review.
Akan
tetapi jika kewenangan memutus Constitutional Complain diberikan
kepada MK dengan cara dimasukkan dalam amandemen UUD 1945 maka akan membutuhkan
waktu yang sangatlah lama. Belum tentu dalam kurun waktu sepuluh tahun yang
akan datang akan terjadi amandemen UUD 1945. Apalagi jika amandemen hanya
bertujuan untuk memasukkan kewenangan memutus Constitutional Complain,
maka akan semakin sulit. Selain itu juga mengamandemen konstitusi harus
memperhatikan struktur, faktor kulrtural dan kondisi negara bersangkutan.
Faktor politis pun juga perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan amandemen. Maka
jalan yang lebih mudah untuk ditempuh adalah dengan cara memasukkan kewenangan
MK dalam memutus Constitutional Complain dalam revisi UU MK.
Merivisi UU tidaklah sesulit mengamandemen konstitusi dasar Indonesia.
Dalam
hal ini kami berpandangan bahwa untuk mempercepat warga negara mendapatkan
perlindungan terhadap hak-hak konstitutionalnya, maka tambahan kewenangan MK
dalam memutus Constitutional Complain lebih baik dimasukkan
terlebih dahulu dalam revisi UU MK. Melakukan revisi UU MK dengan alasan yang sangat
mendesak ini serta menghindari adanya kekosongan tidak akan terlalu membutuhkan
waktu yang sangat lama serta proses yang sulit dibandingkan jika melakukan
amandemen UUD 1945. Akan tetapi ini bukan berarti kewenangan memutus Constitutional
Complain tidak perlu dimasukkan dalam UUD 1945. Tambahan kewenangan ini
harus sejajar dengan kewenangan-kewenangan MK yang sudah termaktub terlebih
dahulu. Oleh karena itu, jika suatu saat nanti amandemen UUD 1945 dilakukan
maka kewenangan memutus Constitutional Complain juga harus ikut
dimasukkan. Akan tetapi, sebelum amandemen itu ada maka harus dilakukan
terlebih dahulu revisi UU MK yang salah satu tujuannya untuk menambahkan
kewenangan MK dalam memutus Constitutional Complain untuk
menjamin hak-hak konstitutional warga negara.
C.
Menggagas Obyek Constitutional Complain
Mahkamah
konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapakan mampu
mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman
yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Melalui
lima kewenangan konstitusional yang dimilikinya, MK harus mengawal UUD 1945
dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokrasi. Keberadaan
MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil,
dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa
lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Oleh karena itu,
selain sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), MK
juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi (the sole interpreter of
constitution) (Fadjar, 2006:119).
Untuk menlengkapi dan memaksimalkan
tugas dan wewenang MK sebagai penjaga dan penafsir tertinggi konstitusi, maka
adanya Constitutional Complain menjadi sebuah keharusan yang ada
pada wewenang MK. Akan tetapi dalam hal ini perlu difikirkan pula hal mana
sajakah yang dapat dijadikan sebagai
obyek dari Constitutional Complain. Jangan kemudian kewenangan
tambahan yang urgent tersebut diberikan tanpa batasan dan aturan yang
jelas.
Apabila melihat pada pengertian yang
dikatakan oleh Mahfudz, MD., maka bisa dilihat dua hal yang menjadi obyek dari
permohonan Constitutional Complain tersebut. Kedua hal tersebut
adalah:
1.
Pengajuan
perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitutional yang tidak ada instrumen
hukum atasnya untuk memperkarakannya.
2.
Pengajuan
perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitutional yang tidak tersedia lagi
atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan).
Kedua hal
diatas merupakan pijakan dasar yang dapat digunakan untuk membatasi obyek
perkara mana sajakah yang masuk dalam lingkup Constitutional Complain.
Selain harus harus memahami obyek
mana sajakah yang menjadi kewenangan dalam Constitutional Complain,
juga perlu diberikan pula adanya aturan dan batasan yang jelas. Aturan dan
batasan ini dapat dikatakan juga sebagai syarat apakah suatu perkara tersebut
dapat dikatan sebagai obyek komplain hak konstitusional ataukah tidak. Aturan
dan batasan ini bisa dilihat dalam peranturan perundang-undangan yang sudah
ada. Diantara aturan dan batasan yang dapat kami simpulkan adalah:
1.
Constitutional Complain berhubungan erat dengan pelanggaran hak
konstitusional warga negara yang tidak ada instrumen hukum untuk menyelesaikannya
atau tidak lagi tersedia jalur penyelesaian hukum. Ini harus dipahami bahwa
setiap warga negara memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh
Undang-undang Dasar, dan ketiadaan instrumen hukum bukan kemudian menjadi
alasan seseorang untuk tidak bisa mendapatkan keadilan.
2.
Constitutional Complain harus lah terhadap perkara yang berupa pelanggaran
langsung terhadap konstitusi dasar negara Indonesia. Ini harus dipahami bahwa
obyek perkara harus bersinggungan langsung dengan hak-hak konstitusional warga
negara yang dijamin UUD 1945, bukan masalah yang bersinggungan dengan
undang-undang di bawah konstitusi. Selain itu juga dapat dipahami bahwa
peraturan di bawah Undang-undang pun jika bertentangan secara langsung dengan
konstitusi dapat dijadikan sebagai obyek Constitutional Complain,
walaupun tidak secara langsung bertentangan dengan undang-undang diatasnya. Hal
ini dikarenakan lembaga kekuasaan kehakimanb yang diberikan wewenang sebagai
penafsir konstitusi hanyalah Mahkamah Konstitusi.
3.
Constitutional Complain merupakan jalan terakhir yang diajukan setelah
tidak tersedia lagi penyelesaian terhadap perkara tersebut. Perlu dipahami
bahwa jalan terakhir yang dimaksud disini bukan hanya melalui penyelesaian
hukum di pengadilan, tetapi juga melalui penyelesaian lain di lembaga
legislatif melalui legislatif review dan penyelesaian di lembaga
eksekutif melalui executive review.
Untuk aturan
dan batasan yang terakhir ini memang harus dicantumkan. Hal ini disebabkan
bahwa Constitutional Complain merupakan langkah terakhir dari
adanya beberapa proses yang telah dilalui sebelumnya. Selain itu ini juga bisa
dijadikan sebagai sebuah kontrol normatif dalam menciptakan sebuah peraturan.
D.
Legislatif Review
dan Execitive Review Sebagai Syarat Constitutional Complain
Seperti
yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa yang menjadi obyek dari Constitutional
Complain adalah semua pelanggaran terhadap langsung terhadap konstitusi
dasar negara Indonesia. Ini harus dipahami bahwa obyek perkara harus bersinggungan
langsung dengan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945,
bukan masalah yang bersinggungan dengan undang-undang di bawah konstitusi.
Selain itu juga dapat dipahami bahwa peraturan di bawah Undang-undang pun jika
bertentangan secara langsung dengan konstitusi dapat dijadikan sebagai obyek Constitutional
Complain, walaupun tidak secara langsung bertentangan dengan
undang-undang diatasnya. Hal ini dikarenakan lembaga kekuasaan kehakiman yang
diberikan wewenang sebagai penafsir konstitusi hanyalah Mahkamah Konstitusi.
Untuk
menghindari menumpuknya persoalan di MK hanya karena sebuah perkara
bertentangan dengan konstitusi atau hak kontitusional warga negara, maka harus
disyaratkan pula bahwa Constitutional Complain merupakan jalan
terakhir yang telah dilalui sebelumnya penyelesaian hukum yang lain. Penumpukan
perkara seperti ini telah terjadi di Mahkamah Konstitusi Federal negara Jerman
yang mana merupakan satu-satunya lembaga
kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan semua persoalan
sengketa perundang-undangan dan konstitusi. Oleh karena itu perlu dipandang
pula bahwa legislative review dan executive review merupakan
langkah penyelesaian yang sudah harus ditempuh oleh seseorang sebelum orang tersebut
mengajukan Constitutional Complain. Hal ini juga berfungsi
sebagai sebuah kontrol normatif terhadap sebuah peraturan yang diperkarakan.
Legislative
review merupakan bagian proses politik di
bidang peraturan perundang-undangan dan lebih dipengaruhi oleh faktor politik
sehingga proses perubahan produk hukum tersebut tidak dilakukan melalui proses judicial
atau dalam koridor normatif yang biasa dijalankan oleh lembaga kekuasaan
kehakiman, melainkan melalui proses politik oleh lembaga politik. Peraturan
perundang-undangan yang diputuskan dan/atau ditetapkan untuk dicabut oleh
pembuatnya, maka secara otomatis pada saat diputuskan/ditetapkan tidak berlaku
lagi, dan pada saat bersamaan lembaga pembuatnya menerbitkan peraturan yang
baru. Berbeda dengan judicial review, bahwa setiap ketentuan
perundang-undangan yang diputus oleh
badan kekuasaan kehakiman, maka ketentuan tersebut tidak berlaku lagi, tetapi
badan kekuasaan kehakiman tidak memutuskan berlakunya peraturan baru, karena
tidak memiliki kewenangan (original jurisdiction) sebagai badan pembuat
undang-undang (Hoesein, 2013:61).
Demikian
pula excutive review diartikan sebagai penilaian atau pengujian
peraturan perundang-undangan oleh pihak eksekutif, artinya segala bentuk produk
hukum pihak eksekutif diuji oleh pihak eksekutif baik kelembagaan dan
kewenangan yang bersifat hierarkis. Dalam istilah yang sama juga diperkenalkan
istilah “kontrol internal”yang dilakukan oleh pihak sendiri terhadap produk
hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk pengaturan (regeling) maupun
penetapan (beschikking). Akan tetapi, jika kontrol normatifnya dilakukan
oleh badan lain dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal tersebut
bukan executive review, melainkan kontrol segi hukum (legal control).
Dalam
hal hubungan ini, maka objek executive review lebih terhadap keputusan
yang bersifat abstrak dan mengatur, serta mengikat secara umum atau dikenal
dengan “regeling”, dan diluar itu yakni yang bersifat “beschikking”
menjadi objek legal control peradilan tata usaha negara. Dengan demikian
semua tindakan atau perbuatan administrasi negara yang dijalankan oleh
pemerintah dapat dikontrol oleh hukum baik secara internal (executive review)
atau secara eksternal, yaitu oleh badan kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini
adalah peradilan tata usaha negara (Hoesein, 2013:62).
Dalam
hubungannya dengan executive review, maka objeknya adalah peraturan
dalam kategori regeling yang dilakukan melalui pendekatan “perubahan”
sebagai ketentuan atau melalui pendekatan “pencabutan” peraturan tertentu dan
menggantinya dengan peraturan baru.
pengujian internal ini disebabkan oleh perubahan norma hukum diatasnya yang
berubah, yakni undang-undangnya berubah atau perubahan sosial yang tidak
diantisipasi oleh peraturan tersebut dan menghendaki untuk diubah. Oleh karena
itu, pengujian internal dalam arti executive review ini dilakukan untuk
menjaga peraturan yang diciptkan oleh pemerintah (eksekutif) tetap sinkron, dan
konsisten segi normatifnya secara vertikal dan terjaga pula tertib hukumnya dan
kepastian hukum, agar rasa keadilan masyarakat atas perubahan sosial-ekonomi
(Hoesein, 2013:63).
BAB
III
PENUTUP
Dari pemaparan diatas setidaknnya
bisa disimpulkan beberapa hal yang juga menjadi rekomendasi:
- Constitutional Complain seyogyanya dimasukkan dalam amandemen UUD 1945. Hal ini dikarenakan karena Constitutional Complain berhubungan erat dengan hak dasar konstituional warga negara dan harus ada pada kewenangan MK, serta sejajar dengan kewenangan MK yang lain yang sudah termaktub dalam UUD 1945. Selain itu juga permasalahan yang ada selama ini belum semuanya dapat diselesaikan dengan melalui kewenangan yang dimiliki MK selama ini, terutama kewenangan Judicial Review. Akan tetapi jika kewenangan memutus Constitutional Complain diberikan kepada MK dengan cara dimasukkan dalam amandemen UUD 1945 maka akan membutuhkan waktu yang sangatlah lama. Belum tentu dalam kurun waktu sepuluh tahun yang akan datang akan terjadi amandemen UUD 1945. Dalam hal ini kami berpandangan bahwa untuk mempercepat warga negara mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak konstitutionalnya, maka tambahan kewenangan MK dalam memutus Constitutional Complain lebih baik dimasukkan terlebih dahulu dalam revisi UU MK. Melakukan revisi UU MK dengan alasan yang sangat mendesak ini serta menghindari adanya kekosongan tidak akan terlalu membutuhkan waktu yang sangat lama serta proses yang sulit dibandingkan jika melakukan amandemen UUD 1945. Akan tetapi ini bukan berarti kewenangan memutus Constitutional Complain tidak perlu dimasukkan dalam UUD 1945. Tambahan kewenangan ini harus sejajar dengan kewenangan-kewenangan MK yang sudah termaktub terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika suatu saat nanti amandemen UUD 1945 dilakukan maka kewenangan memutus Constitutional Complain juga harus ikut dimasukkan. Akan tetapi, sebelum amandemen itu ada maka harus dilakukan terlebih dahulu revisi UU MK yang salah satu tujuannya untuk menambahkan kewenangan MK dalam memutus Constitutional Complain untuk menjamin hak-hak konstitutional warga negara.
3.
Adanya
Constitutional Complain menjadi sebuah keharusan yang ada pada
wewenang MK maka perlu difikirkan pula hal mana sajakah yang dapat dijadikan sebagai obyek dari Constitutional
Complain. Jangan kemudian kewenangan tambahan yang urgent
tersebut diberikan tanpa batasan dan aturan yang jelas. Dari pengertian yang
dikatakan oleh Mahfudz, MD., maka bisa dilihat dua hal yang menjadi obyek dari
permohonan Constitutional Complain tersebut, yaitu: Pengajuan
perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitutional yang tidak ada instrumen
hukum atasnya untuk memperkarakannya dan Pengajuan perkara ke MK atas
pelanggaran hak konstitutional yang tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian
hukum (peradilan).
4.
Selain
harus harus memahami obyek mana sajakah yang menjadi kewenangan dalam Constitutional
Complain, juga perlu diberikan pula adanya aturan dan batasan yang
jelas. Aturan dan batasan ini dapat dikatakan juga sebagai syarat apakah suatu
perkara tersebut dapat dikatan sebagai obyek komplain hak konstitusional
ataukah tidak. Aturan dan batasan ini bisa dilihat dalam peranturan
perundang-undangan yang sudah ada. Diantara aturan dan batasan yang dapat kami
simpulkan adalah:
a. Constitutional Complain berhubungan erat dengan pelanggaran hak
konstitusional warga negara yang tidak ada instrumen hukum untuk
menyelesaikannya atau tidak lagi tersedia jalur penyelesaian hukum.
b. Constitutional Complain harus lah terhadap perkara yang berupa
pelanggaran langsung terhadap konstitusi dasar negara Indonesia secara
langsung.
c. Constitutional Complain merupakan jalan terakhir yang diajukan setelah
tidak tersedia lagi penyelesaian terhadap perkara tersebut.
5.
Perlu
dipahami bahwa jalan terakhir yang dimaksud disini bukan hanya melalui
penyelesaian hukum di pengadilan, tetapi juga melalui penyelesaian lain di
lembaga legislatif melalui legislatif review dan penyelesaian di lembaga
eksekutif melalui executive review. Untuk aturan dan batasan yang
terakhir ini memang harus dicantumkan. Hal ini disebabkan bahwa Constitutional
Complain merupakan langkah terakhir dari adanya beberapa proses yang
telah dilalui sebelumnya. Selain itu, ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah
kontrol normatif dalam menciptakan sebuah peraturan
Daftar
Pustaka
Fadjar, Abdul Mukthie. 2006. Hukum
Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
Hoesein, Zainal Arifin. 2013. Judicial
Review Di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
Mahfud MD, MOH. 2010. Konstitusi
Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
*Makalah ini disampaikan dalam Eliminasi Debat Kontitusi Mahasiswa Nasional Antar Perguruan Tinggi tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 24-26 Mei 2015.